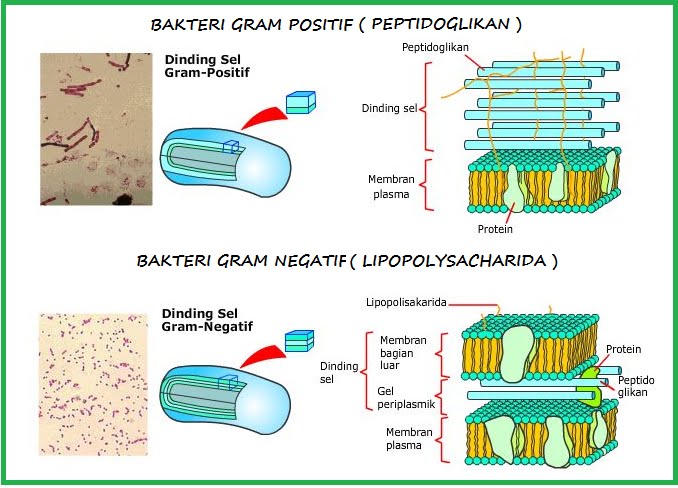Bioetanol
1. Pengertian Bioetanol
Bioetanol merupakan bahan kimia berupa
alkohol yang diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung zat pati.
Bioetanol secara umum digunakan sebagai bahan baku industri turunan alkohol,
campuran untuk miras, bahan dasar industri farmasi, campuran bahan bakar
kendaraan.
Mengingat manfaatnya tersebut yang
beragam, sehingga grade etanol yang dimanfaatjkan harus berbeda, sesuai dengan
penggunaannya. Untuk
ethanol/bio-ethanol yangmempunyai grade 90-96,5% vol dapat digunakan
pada industri, sedangkan ethanol/bioethanol yang mempunyai grade 96-99,5%
vol dapat digunakan sebagai campuran untuk miras dan bahan dasar industri
farmasi. Berlainan dengan besarnya grade ethanol/bioethanol yang
dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan yang harus
betul-betul kering dan anhydrous supaya tidak korosif, sehingga
ethanol/bio-ethanol harus mempunyai grade sebesar 99,5-100% vol.
Perbedaan besarnya grade akan berpengaruh terhadap proses konversi
karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air. (Indya.M,2006:75)
2.
PROSES
PRODUKSI BIO-ETHANOL
Produksi ethanol/bio-ethanol (alkohol)
dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohydrat, dilakukan
melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula (glukosa) larut air. Konversi
bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohydrat dan tetes menjadi
bio-ethanol.
Glukosa
dapat dibuat dari pati-patian, proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan
zat pembantu yang dipergunakan, yaitu Hydrolisa asam dan Hydrolisa enzyme.
Berdasarkan kedua jenis hydrolisa tersebut, saat ini hydrolisa enzyme lebih
banyak dikembangkan, sedangkan hydrolisa asam (misalnya dengan asam sulfat) kurang
dapat berkembang, sehingga proses pembuatan glukosa dari pati-patian sekarang
ini dipergunakan dengan hydrolisa enzyme. Dalam proses konversi karbohidrat
menjadi gula (glukosa) larut air dilakukan dengan penambahan air dan enzyme;
kemudian dilakukan proses peragian atau fermentasi gula menjadi ethanol dengan
menambahkan yeast atau ragi.
H2O(C6H10O5)n -----------------àN C6H12O6 (2)
enzyme(pati) (glukosa)
(C6H12O6)n ---------------------à 2 C2H5OH + 2 CO2. (3)
(glukosa) yeast
(ragi) (ethanol)
Selain ethanol/bio-ethanol dapat
diproduksi dari bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohydrat, juga
dapat diproduksi dari bahan tanaman yang mengandung selulosa, namun dengan
adanya lignin mengakibatkan proses penggulaannya menjadi lebih sulit, sehingga
pembuatan ethanol/bio-ethanol dari selulosa tidak perlu direkomendasikan.
Meskipun teknik produksi ethanol/bioethanol merupakan teknik yang sudah lama
diketahui, namun ethanol/bio-ethanol untuk bahan bakar kendaraan memerlukan
ethanol dengan karakteristik tertentu yang memerlukan teknologi yang relatif
baru di Indonesia antara lain mengenai neraca energi (energy balance)
dan efisiensi produksi, sehingga penelitian lebih lanjut mengenai teknologi
proses produksi ethanol masih perlu dilakukan. Secara singkat teknologi proses
produksi ethanol/bio-ethanol tersebut dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu
gelatinasi, sakharifikasi, dan fermentasi.
a.
Proses
Gelatinasi
Dalam proses gelatinasi, bahan baku
dihancurkan dan dicampur air sehingga menjadi bubur, yang diperkirakan mengandung
pati 27-30 persen. Kemudian bubur pati tersebut dimasak atau dipanaskan selama
2 jam sehingga berbentuk gel. Proses gelatinasi tersebut dapat dilakukan dengan
2 cara, yaitu:
1.
Bubur
pati dipanaskan sampai 1300C selama 30 menit, kemudian didinginkan
sampai mencapai temperature 950C yang diperkirakan memerlukan waktu
sekitar ¼ jam. Temperatur 950C tersebut dipertahankan selama sekitar
1 ¼ jam, sehingga total waktu yang dibutuhkan mencapai 2 jam.
2.
Bubur
pati ditambah enzyme termamyl dipanaskan langsung sampai mencapai temperatur
1300C selama 2 jam.
Gelatinasi cara pertama, yaitu cara
pemanasan bertahap mempunyai keuntungan, yaitu pada suhu 950C
aktifitas termalnya merupakan yang paling tinggi, sehingga mengakibatkan yeast
atau ragi cepat aktif. Pemanasan dengan suhu tinggi (1300C) pada cara pertama ini
dimaksudkan untuk memecah granula pati, sehingga lebih mudah terjadi kontak
dengan air enzyme. Perlakuan pada suhu tinggi tersebut juga dapat berfungsi
untuk sterilisasi bahan, sehingga bahan tersebut tidak mudah terkontaminasi. Gelatinasi
cara kedua, yaitu cara pemanasan langsung (gelatinasi dengan enzyme termamyl)
pada temperature 130oC menghasilkan hasil yang kurang baik, karena mengurangi
aktifitas yeast. Hal tersebut disebabkan gelatinasi dengan enzyme pada
suhu 1300C akan terbentuk tri-phenyl-furane yang mempunyai sifat racun
terhadap yeast. Gelatinasi pada suhu tinggi tersebut juga akan berpengaruh
terhadap penurunan aktifitas termamyl, karena aktifitas termamyl akan semakin
menurun setelah melewati suhu 950C. Selain itu, tingginya temperature
tersebut juga akan mengakibatkan half life dari termamyl semakin pendek,
sebagai contoh pada temperature 930C, half life dari termamyl
adalah 1500 menit, sedangkan pada temperature 1070C, half life termamyl
tersebut adalah 40 menit (Wasito, 1981). Hasil gelatinasi dari ke dua cara
tersebut didinginkan sampai mencapai 550C, kemudian ditambah SAN
untuk proses sakharifikasi dan selanjutnya difermentasikan dengan menggunakan yeast
(ragi) Saccharomyzes ceraviseze.
b.
Fermentasi
Proses fermentasi dimaksudkan
untuk mengubah glukosa menjadi ethanol/bio-ethanol (alkohol) dengan menggunakan
yeast. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini, biasanya alkohol
dengan kadar 8 sampai 10 persen volume. Sementara itu, bila fermentasi tersebut
digunakan bahan baku gula (molases), proses pembuatan ethanol dapat lebih
cepat. Pembuatan ethanol dari molases tersebut juga mempunyai keuntungan lain,
yaitu memerlukan bak fermentasi yang lebih kecil. Ethanol yang dihasilkan
proses fermentasi tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya dengan
membersihkannya dari zat-zat yang tidak diperlukan.
Alkohol yang dihasilkan dari proses
fermentasi biasanya masih mengandung gasgas antara lain CO2 (yang ditimbulkan
dari pengubahan glucose menjadi ethanol/bio-ethanol) dan aldehyde yang perlu
dibersihkan. Gas CO2 pada hasil fermentasi tersebut biasanya mencapai 35 persen
volume, sehingga untuk memperoleh ethanol/bio-ethanol yang berkualitas baik,
ethanol/bio-ethanol tersebut harus dibersihkan dari gas tersebut. Proses
pembersihan (washing) CO2 dilakukan dengan menyaring ethanol/bio-ethanol
yang terikat oleh CO2, sehingga dapat diperoleh ethanol/bio-ethanol yang bersih
dari gas CO2). Kadar ethanol/bio-ethanol yang dihasilkan dari proses
fermentasi, biasanya hanya mencapai 8 sampai 10 persen saja, sehingga untuk
memperoleh ethanol yang berkadar alkohol 95 persen diperlukan proses lainnya,
yaitu proses distilasi. Proses distilasi dilaksanakan melalui dua tingkat,
yaitu tingkat pertama dengan beer column dan tingkat kedua dengan rectifying
column. Definisi kadar alkohol atau ethanol/bio-ethanol dalam % (persen)
volume adalah “volume ethanol pada temperatur 150C yang terkandung
dalam 100 satuan volume larutan ethanol pada temperatur tertentu (pengukuran).“
Berdasarkan BKS Alkohol Spiritus, standar temperatur pengukuran adalah 27,5o C
dan kadarnya 95,5% pada temperatur 27,50C atau 96,2% pada temperatur
150C.
Pada umumnya hasil fermentasi adalah
bio-ethanol atau alkohol yang mempunyai kemurnian sekitar 30 – 40% dan belum
dpat dikategorikan sebagai fuel based ethanol. Agar dapat mencapai kemurnian
diatas 95% , maka lakohol hasil fermentasi harus melalui proses destilasi.
c.
Distilasi
:
Sebagaimana disebutkan diatas, untuk
memurnikan bioetanol menjadi berkadar lebih dari 95% agar dapat dipergunakan
sebagai bahan bakar, alkohol hasil fermentasi yang mempunyai kemurnian sekitar
40% tadi harus melewati proses destilasi untuk memisahkan alkohol dengan air
dengan memperhitungkan perbedaan titik didih kedua bahan tersebut yang kemudian
diembunkan kembali.
Untuk memperoleh bio-ethanol dengan
kemurnian lebih tinggi dari 99,5% atau yang umum disebut fuel based ethanol,
masalah yang timbul adalah sulitnya memisahkan hidrogen yang terikat dalam
struktur kimia alkohol dengan cara destilasi biasa, oleh karena itu untuk
mendapatkan fuel grade ethanol dilaksanakan pemurnian lebih lanjut dengan cara
Azeotropic destilasi. (Indyah.M,2006:75-79)
BAMBU
Bambu merupakan tumbuhan yang biasa digunakan untuk kontruksi
bangunan, perabot rumah tangga sampai menjadi karya seni. Namun, bambu juga
dapat dijadikan sebagai bio-etanol sebagai alternatif dalam krisis energi pada
saat. Oleh karena itu, perlu adanya budidaya bambu untuk dapat meningkatkan
jumlah bambu yang akan diolah menjadi bio-etanol.
Bambu merupakan jenis
rumput-rumputan yang berbentuk pohon kayu atau perdu melempeng. Pertumbuhan
tunas bambu atau rebung, ada yang tumbuh sepanjang musim, ada juga yang tumbuh
diawal musim hujan atau diakhir musim hujan (Heyne 1987). Pertumbuhan rebung
ini menjadi awal dari petumbuhan bambu. Rebung ini nantinya akan berubah
menjadi buluh-buluh bambu yang tidak lagi diselimuti oleh seludang.
Setelah
rebung-rebung tersebut berubah menjadi buluh maka pertumbuhan selanjutnya
adalah pembentukan cabang dan pengayuan batang dengan penebalan dinding (Heyne
1987). Selain itu Heyne juga menjelaskan bahwa pertumbuhan cabang-cabang
tersebut terjadi pada tahun kedua dan di tahun ketiga seludang-seludang
tersebut akan luruh dan batang-batangnya akan ditumbuhi lumut. Kemudian selang tiga sampai empat tahun lagi buluh bambu
tersebut dapat dipanen. (Fajriyah dan Yenny Astriana Fitriatul,2012:6)
Budidaya Bambu
Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadaek (2009) teknik budidaya bambu
meliputi persiapan tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan,
pengendalian hama dan penyakit, dan penebangan (pemanenan) Persiapan tanam
merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan penanaman. Nadaek
(2009) menjelaskan bahwa persiapan tanam dapat dimulai dengan membuat lubang
tanam secukunya (disesuaikan dengan kondisi akar stek). Biasanya, lubang tanam
dibuat dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm sampai 50 x 50 x 50 cm dengan jarak tanam
3 x 3 m, 4 x 4 m, atau 5 x 5 m atau dapat disesuaikan dengan ukuran buluh dalam
rumpun. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan karena pertumbuhan awal bambu
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air. Penanaman dilakukan dengan bibit stek
batang ditanam horizontal atau miring sekitar 45 derajat dan bagian tunasnya
menghadap kearah atas. Bila bibit tunasnya sudah tumbuh, ditanam tegak.
Pemeliharaan
dimulai dengan kegiatan penyulaman yang dilakukan pada tahun pertama. Kemudian
dilakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang terlalu rendah. Sedangkan menurut
Nadaek (2009) selain kegiatan penyulaman dan pemangkasan, penjarangan buluh
juga dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan. Pemangkasan buluh ini dilakukan
pada buluh yang tumbuh tidak normal, berhimpit dan buluh yang tumbuh tidak
produktif.
Pemupukan
dilakukan dengan menggunakan pupuk urea yang berguna untuk mempercepat
pertumbuhan buluh bambu dan serasah daun sebagai pucuk alami yang juga dapat
membantu pertumbuhan tanaman. Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan
15-15-15 NPK (masing-masing 100, 100, 200 kg/ha) . Pemberian jenis dan dosis
pupuk disesuaikan dengan umur dari bambu itu sendiri. (Fajriyah dan
Yenny Astriana Fitriatul,2012:7)
KLASIFIKASI
BAMBU
Bambu
khususnya di Indonesia memiliki jenis yang berbeda-beda. Sehingga kandungan
yang terdapat pada bambu tersebut itupun berbeda. Klasifikasi bambu dan unsur
yang yang dikandung yaitu:
Bambu menurut tempat
tumbuh
Bambu asal Bulria
-
Lignin 27,17%
-
Holoselulosa
75,57%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,70%
-
Larut air panas 6,23%
-
Diameter lumen 3,10 mikron
-
Diameter serat 0,91 mikron
-
Sel pori 12,39%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,74%
-
Alfa-Selulosa 44,22%
-
Sel serat 32,31%
-
Sel parenkim 55,44%
-
Tebal dinding sel 0,91 mikron
-
Panjang Serat 3,79 mikron
Bambu Asal Morekau
-
Lignin 72,31%
-
Holoselulosa 26,42%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,61%
-
Larut air panas 5,77%
-
Diameter lumen 2,92 mikron
-
Diameter serat 0,76 mikron
-
Sel pori 14,33%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,79%
-
Alfa-selulosa 44,91%
-
Sel serat 62,64%
-
Sel parenkim 53,10%
-
Tebal dinding sel 0,76 mikron
-
Panjang Serat 3,56 mikron
Bambu asal Tala
-
Lignin 72,68%
-
Holoselulosa 26,0%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,32%
-
Larut air panas 5,50%
-
Diameter lumen 2,98 mikron
-
Diameter serat 0,80 mikron
-
Sel pori 14,05%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,45%
-
Alfa-selulosa 45,76%
-
Sel Serat 29,99%
-
Sel parenkim 56,71%
-
Tebal dinding sel 0,80 mikron
-
Panjang Serat 3,70 mikron
Bambu menurut Jenis
Bambu Petung
-
Lignin 27,37%
-
Holoselulosa 76,63%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,59%
-
Larut air panas 5,92%
-
Diameter lumen 3,10 mikron
-
Diameter serat 4,91mikron
-
Sel pori 12,58%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 4,1%
-
Alfa-selulosa 44,94%
-
Sel serat 32,64%
-
Sel parenkim 54,79%
-
Tebal dinding sel 0,90 mikron
-
Panjang Serat 3,90 mikron
Bambu Sero
-
Lignin 26,18%
-
Holoselulosa 71,96%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,46%
-
Larut air panas 5,88%
-
Diameter lumen 3,00 mikron
-
Diameter serat 4,60 mikron
-
Sel pori 14,96%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,43%
-
Alfa-selulosa 44,30%
-
Sel serat 29,03%
-
Sel parenkim 56,85%
-
Tebal dinding sel 0,80%
-
Panjang Serat 3,55 mikron
Bambu Tui
-
Lignin 26,05%
-
Holoselulosa 75,77%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,59%
-
Larut air panas 5,70%
-
Diameter lumen 2,90 mikron
-
Diameter serat 4,44 mikron
-
Sel pori 13,23%
-
Eksteraktif larut alkohol benzen 3,49%
-
Alfa-selulosa 45,56%
-
Sel serat 33,30%
-
Sel parenkim 53,61%
-
Tebal dinding sel 0,77 mikron
-
Panjang Serat 3,57 mikron
Berdasarkan Posisi batang
Pangkal
-
Lignin 26,67%
-
Holoselulosan 72,54%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,59%
-
Larut air panas 6,52%
-
Diameter lumen 3,23 mikron
-
Diameter serat 4,97 mikron
-
Sel pori 14,60%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,89%
-
Alfa-selulosa 46,04%
-
Sel Serat 27,81%
-
Sel parenkim 56,83%
-
Tebal dinding sel 0,91 mikron
-
Panjang Serat 3,96 mikron
Tengah
-
Lignin 26,67%
-
Holoselulosa 73,14%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,65%
-
Larut air panas 5,44%
-
Diameter lumen 3,02%
-
Diameter serat 4,72%
-
Sel pori 13,34%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,82%
-
Alfa-selulosa 44,98%
-
Sel serat 31,84%
-
Sel parenkim 55,67%
-
Tebal dinding sel 0,80 mikron
-
Panjang Serat 3,67 mikron
Ujung
-
Lignin 26,36%
-
Holoselulosa 72,67%
-
Ekstraktif larut air dingin 3,30%
-
Larut air panas 5,43%
-
Diameter lumen 2,74 mikron
-
Diameter serat 4,34 mikron
-
Sel pori 13,13%
-
Ekstraktif larut alkohol benzen 3,37%
-
Alfa selulosa 43,89%
-
Sel serat 35,31%
-
Sel parenkim 51,95%
-
Tebal dinding sel 0,77 mikron
-
Panjang Serat 3,40 mikron (E. Manuhuwa dan M. Loiwatu,2007:5-6)
Dari tersebut dapat
kesimpulan, bahwa bambu:
1.
Lokasi
yang berbeda memberikan interaksi yang signifikan terhadap kandungan lignin
bambu, diameter serat, diameter lumen, dan proporsi sel parensim.
2.
Jenis
bambu yang berbeda memberikan interaksi yang signifikan terhadap panjang dan
diameter sel serat.
3.
Posisi
batang bambu yang berbeda memberikan interaksi yang signifikan terhadap
ekstraktif larut panas, ekstraktif larut alkohol benzen, panjang dan diameter serat,
serta diameter lumen.
4.
Rata-rata
ekstraktif larut air dingin bambu berkisar antara 3,10%-3,79%; ekstraktif larut
air panas 5,43%-6,23%; ekstraktif larut alkohol benzen 3,37%-4,10%; alfa
selulosa 44,22%- 46,94%; holoselulosa 71,97%-75,57%; lignin 26,00%-27,37%.
5.
Rata-rata
panjang sel serat bambu berkisar antara 3,40mm-3,96mm; diameter serat
4,34mikron-4,91mikron; diameter lumen 2,74mikron-3,23mikron; tebal dinding sel
serat 0,76mikron-0,91mikron; proporsi sel parensim 51,95%-56,85%; proporsi sel
serat 27,81%- 62,66%, dan proporsi sel pori 12,39%-14,60%. (E. Manuhuwa dan M. Loiwatu,2007:15)